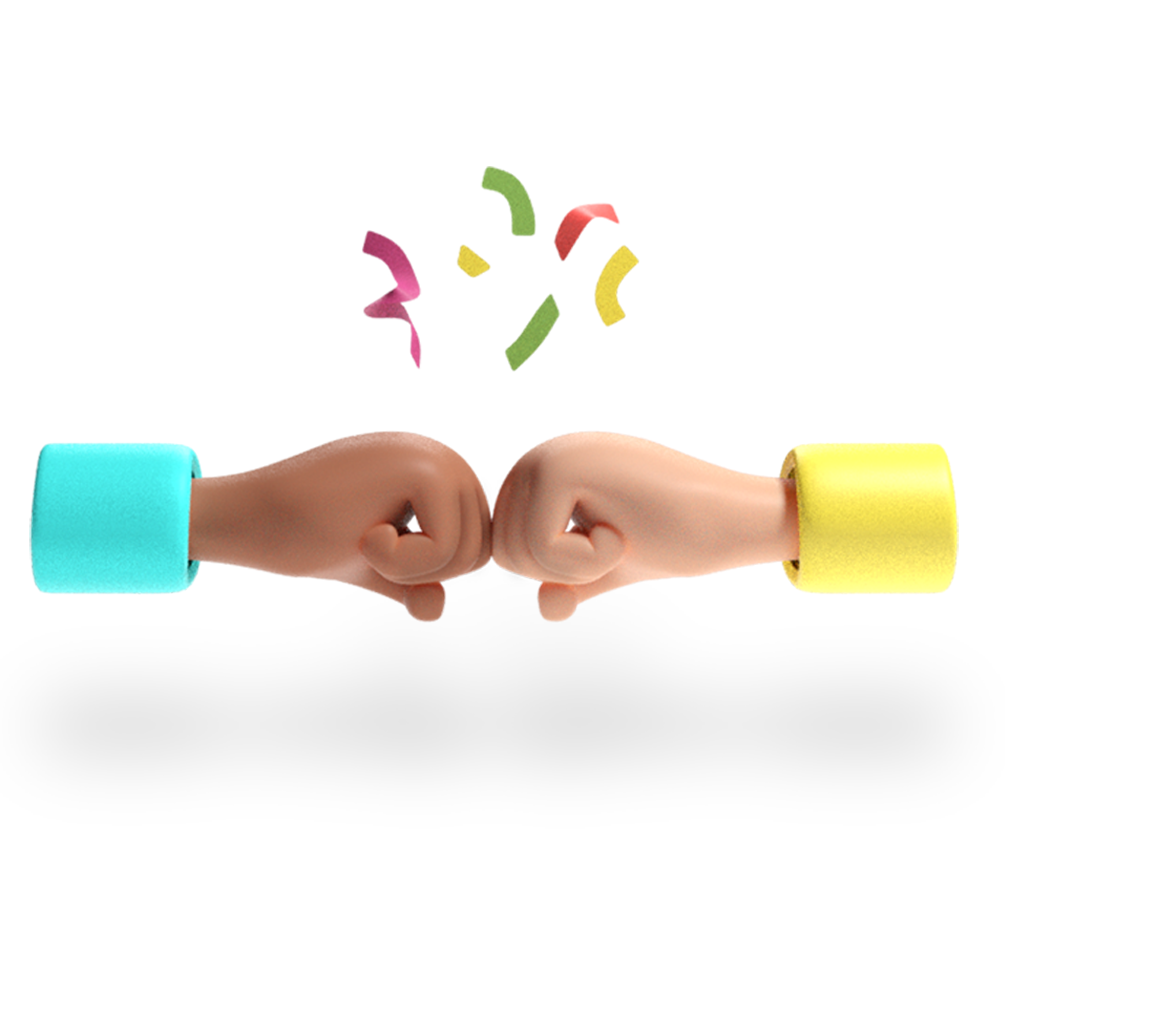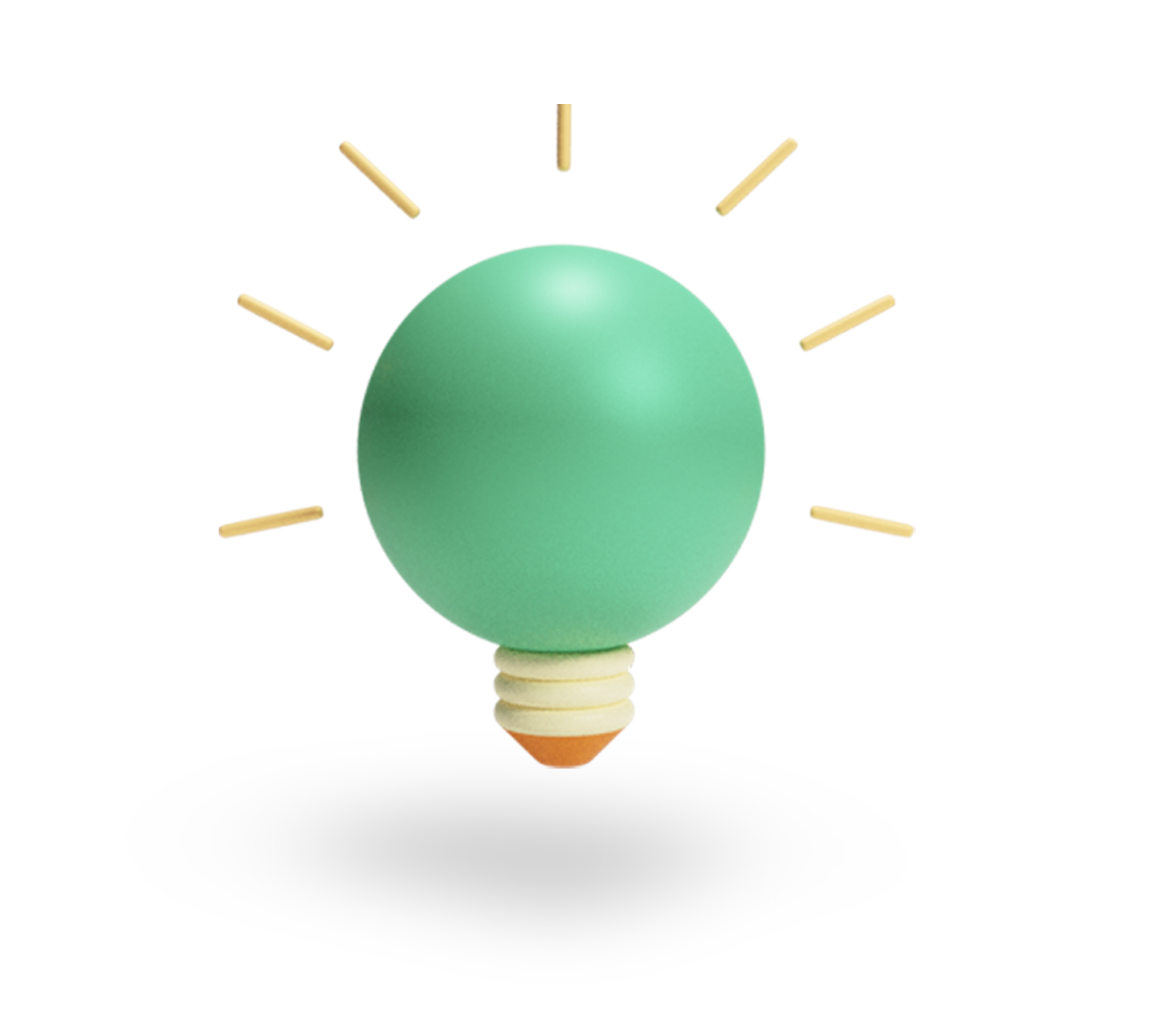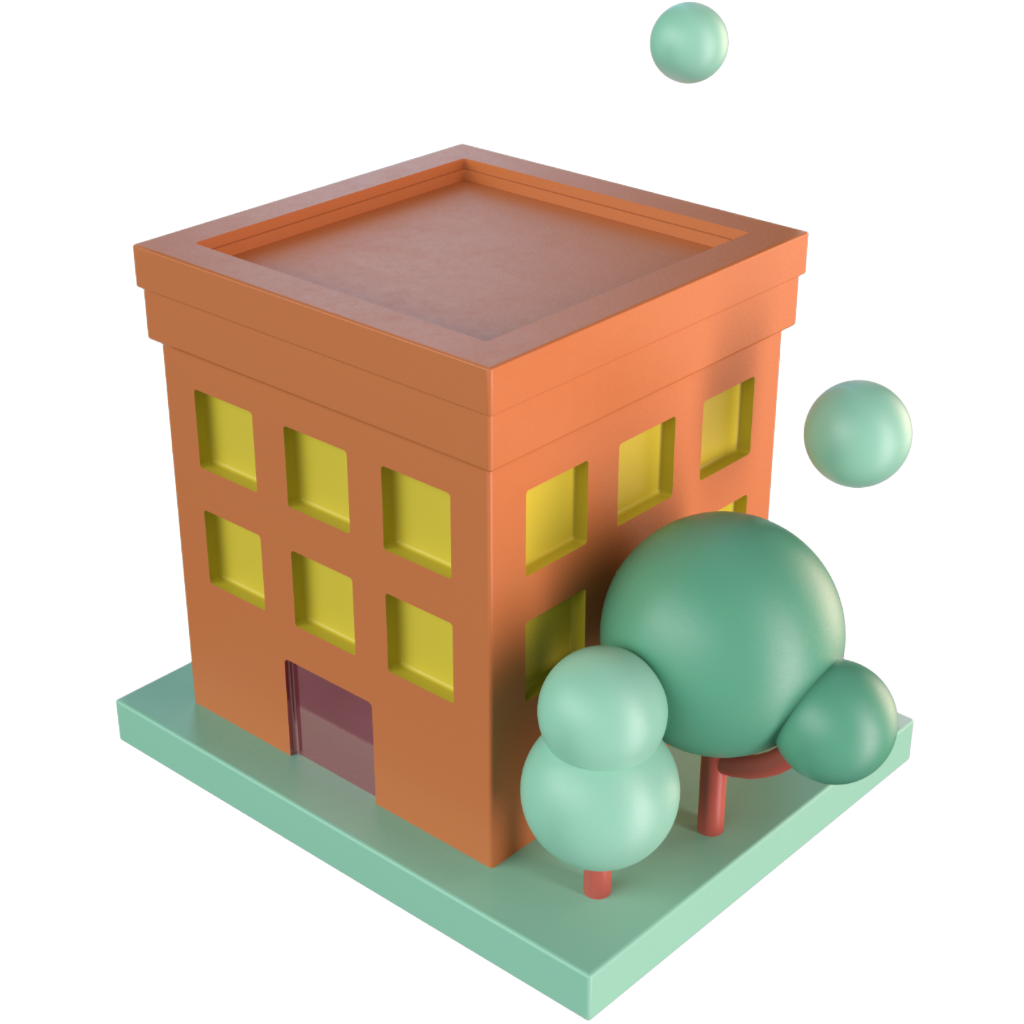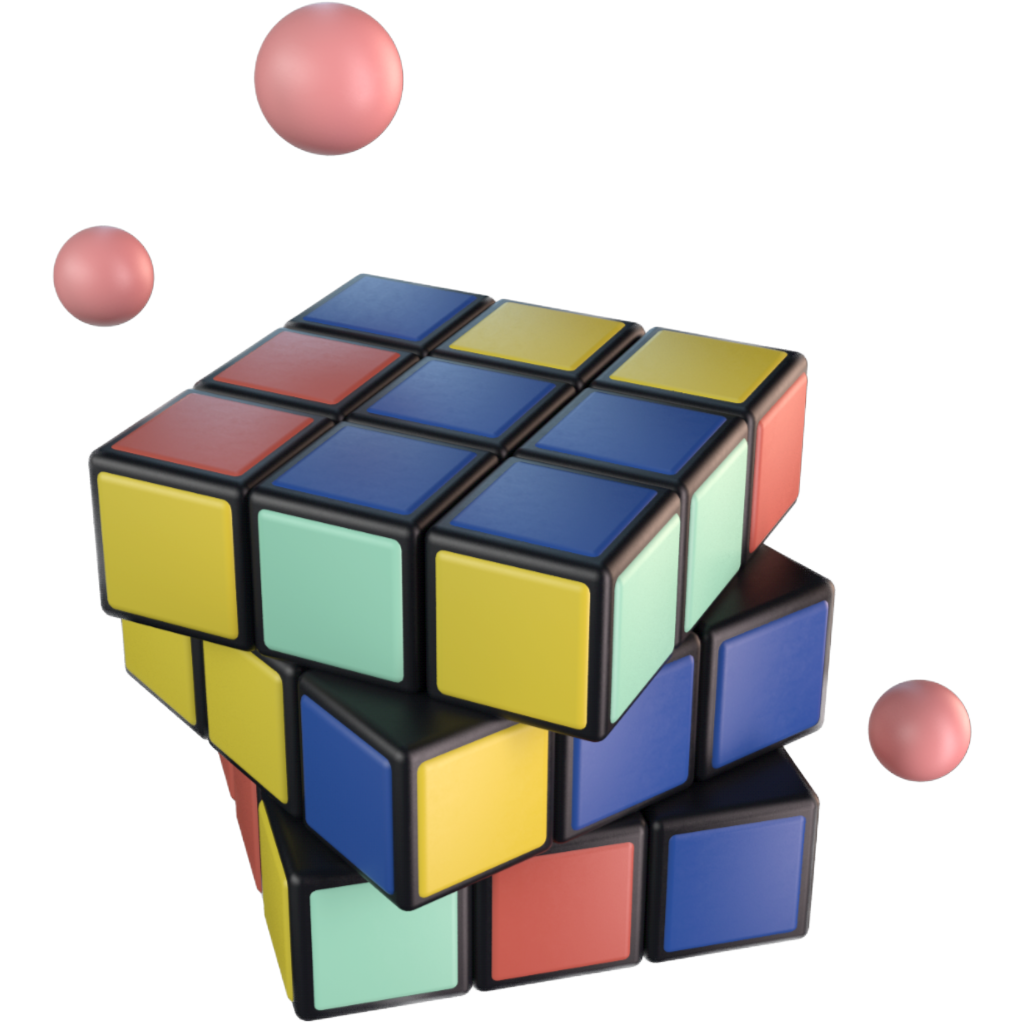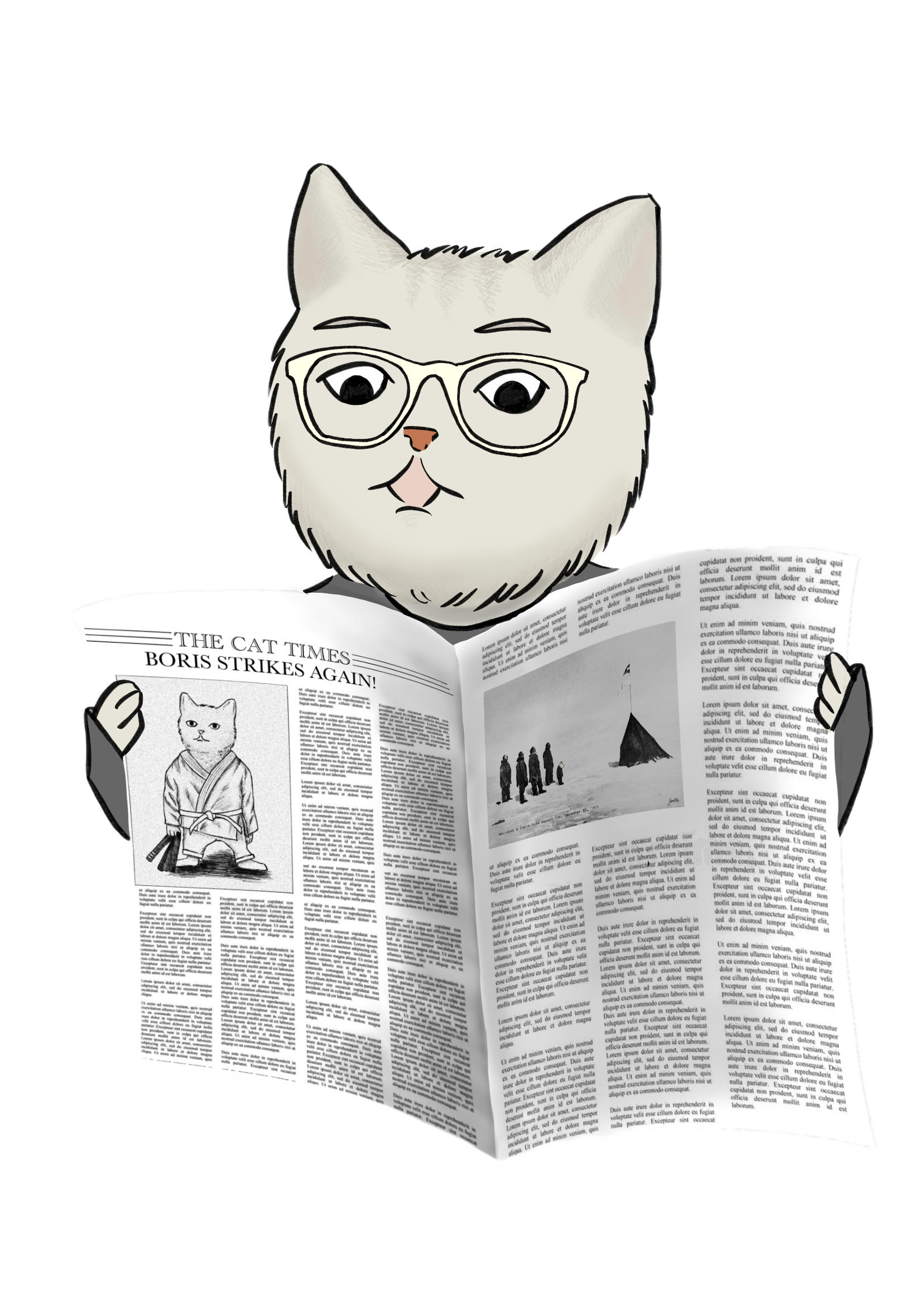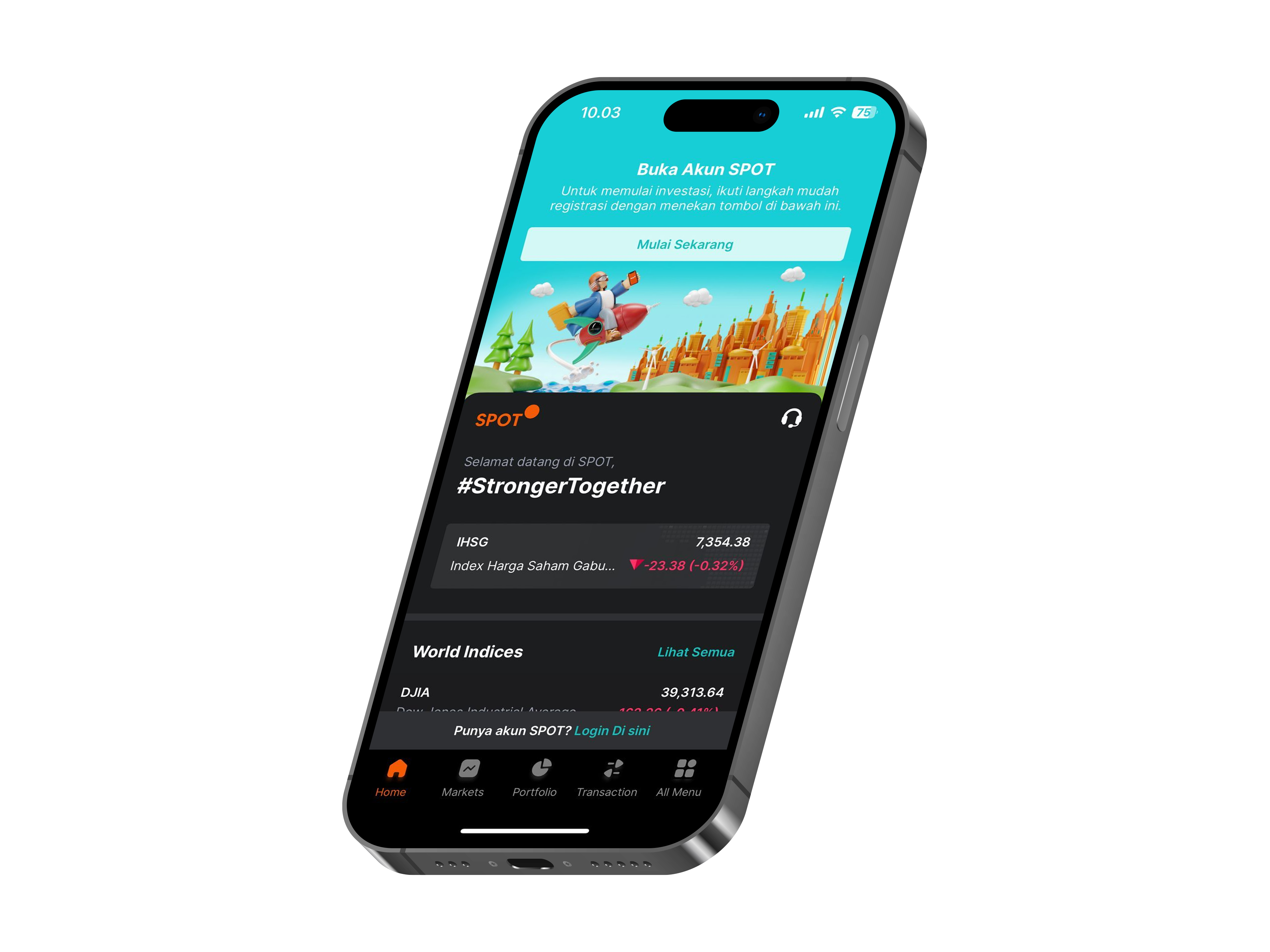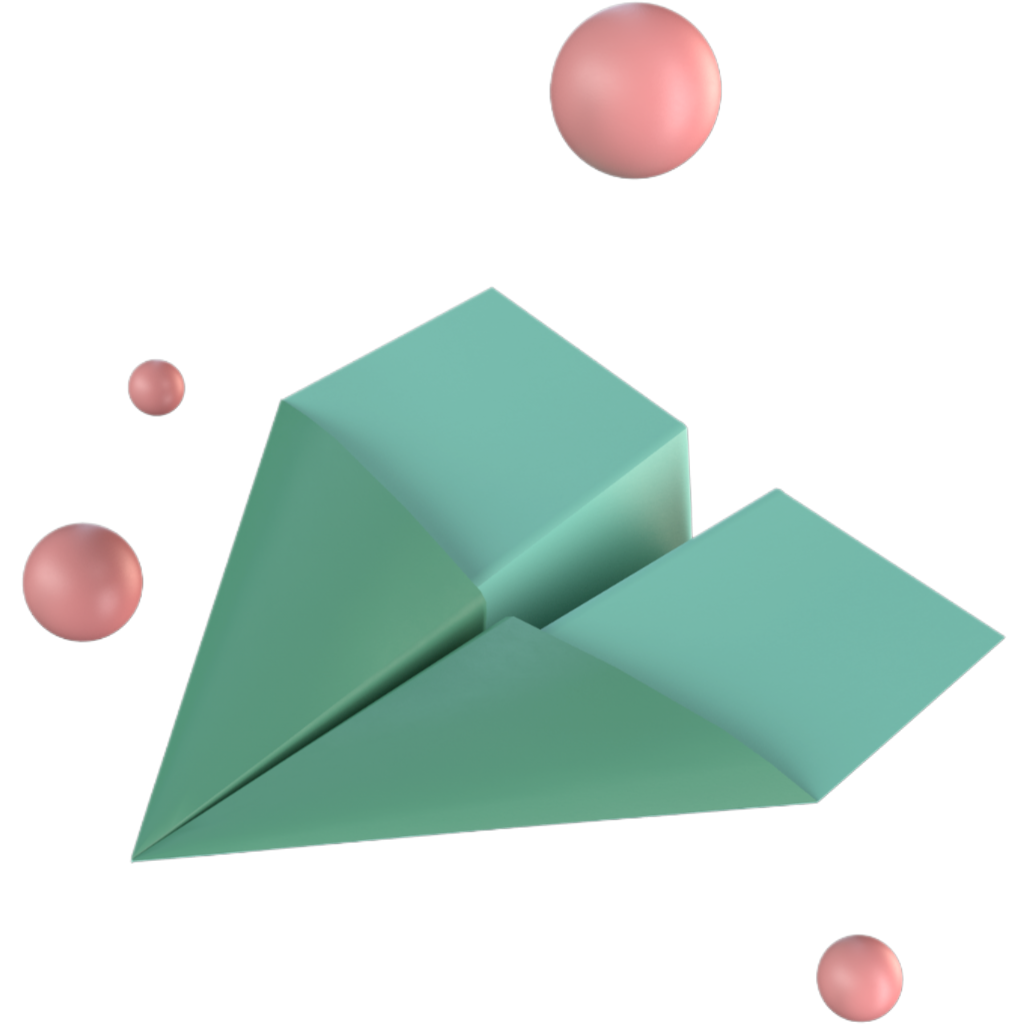Diam-diam aku menyimpan rasa kagum akan arsitektur jaman dulu yang masih tersisa di daerah Cikini. Antara interior cafe dan trotoar hanya dipisahkan oleh jendela kaca. Terbayang bagaimana nonik-nonik Belanda di era itu sedang minum teh atau menyeruput kopi sembari bertukar gosip. Tidak tergesa untuk menyelesaikan pekerjaan, tanpa ada pesan WA atau email yang menagih untuk segera dijawab. Jujur, ada sedikit rasa iri yang menyeruak.
Sedang asyik bercengkrama dengan pikiranku sendiri, entah muncul dari mana, seorang bapak tua mendekat dan berkata:
“Pak, saya sebenarnya malu untuk bilang…saya perlu sedikit uang untuk pulang ke rumah naik kereta dari stasiun Gondangdia. Tapi dompet saya benar-benar kosong, Pak. Tolong saya untuk bisa pulang.”
Ada nada putus asa dari si lelaki itu ketika menunjukkan dompet kumal yang memang kosong.
Mungkin karena merasa lamunanku terganggu, aku jawab “Maaf Pak ya…” Secara otomatis aku juga berpikir bahwa ini pasti satu lagi bentuk penipuan di Jakarta tercinta.
Seolah bisa membaca pikiranku, si lelaki itu merasa tidak enak dan bilang “Maaf ya Pak telah mengganggu…benar-benar maaf”.
Kemudian lelaki itu menggeleng dan berjalan menjauh. Sulit ditebak, si lelaki itu menggeleng karena apa. Mungkin sedang kecewa pada dirinya sendiri. Mungkin juga sedang sangat putus asa. Entah.
Sekitar lima menit-an kemudian, rasa menyesal mulai datang menghampiri. Ada yang janggal, yang tidak biasa. Lelaki tadi tidak memaksa. Malah minta maaf. Dan sorot matanya sedang mengkonfirmasi bahwa ia malu berbuat demikian. Atau mungkin ia aktor jempolan. Mana aku tahu.
Dilanda bingung campur penyesalan, akupun berbalik dan berusaha mencari lelaki itu. Namun ia telah menghilang, seolah punya ilmu ninja.
Ya sudah, akupun berbalik lagi, melanjutkan perjalananku. Kali ini aku tidak melongok etalase cantik di sepanjang jalan Cikini. Yang ada malahan wajah sedih si lelaki tadi, yang terus terbayang. Dan terus aku bertanya pada diri sendiri “Bagaimana kalau si Bapak tadi beneran nggak bisa pulang rumah?”
Harusnya aku lebih memakai hati. Sekali-sekali coba dengarkan suara hati dan beri si lelaki itu sedikit uang. Namun, sekarang sudah terlambat.
Kadang menjadi “orang Jakarta”, nurani kita jadi mati. Karena terlalu sering ditipu dan dibohongi. Ketakutan dibohongi, menjadi lebih besar dari keberanian membuka diri dari suara hati sendiri. Sejenak aku terdiam. Tenggelam dalam pikiran. Tapi kali ini bukan pikiran tentang nonik-nonik Belanda.
Kali ini aku berpikir soal budaya dalam organisasi. Dalam sebuah organisasi di mana kultur yang ada berfokus pada politik kantor yang sarat dengan saling tikam dari depan, samping, dan belakang. Walhasil, para anggota organisasi akan disibukkan dengan aksi “membangun pagar” untuk membentengi diri masing-masing. Demi survival, suara hati harus dipinggirkan dulu, Mau gimana lagi.
Sebaliknya, dalam sebuah organisasi di mana kita saling peduli satu sama lain, dan anggotanya saling berkomunikasi secara sungguh dan tulus, kita akan turut menjadi bagian hidup sesama anggota organisasi. Komunitas dalam arti yang dalam dan sesungguhnya. Kita semua ingin menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar daripada diri kita. Kita merasa aman, dan bahagia. Akhirnya kita nyaman dan berani menjadi diri kita sendiri.
Keberanian menjadi diri sendiri ini bermuara pada keinginan untuk membangun jembatan. Bukan membangun pagar yang membentengi hati nurani. Bisikan hati yang membuat kita tidak menjadi “orang Jakarta” yang takut berlebihan untuk ditipu. Bisikan hati yang membuat kita kembali bersedia untuk menjadi pendengar yang baik buat sekedar kisah sesama kita.
Aku sedang kembali mengingatkan diri bahwa mendengarkan dengan atensi dan apresiasi adalah kunci hubungan sosial yang baik. Kunci jembatan sosial. Jembatan yang akan membawa kita tiba pada kebahagiaan, sukses, kesehatan, dan banyak hal-hal manis dalam hidup.