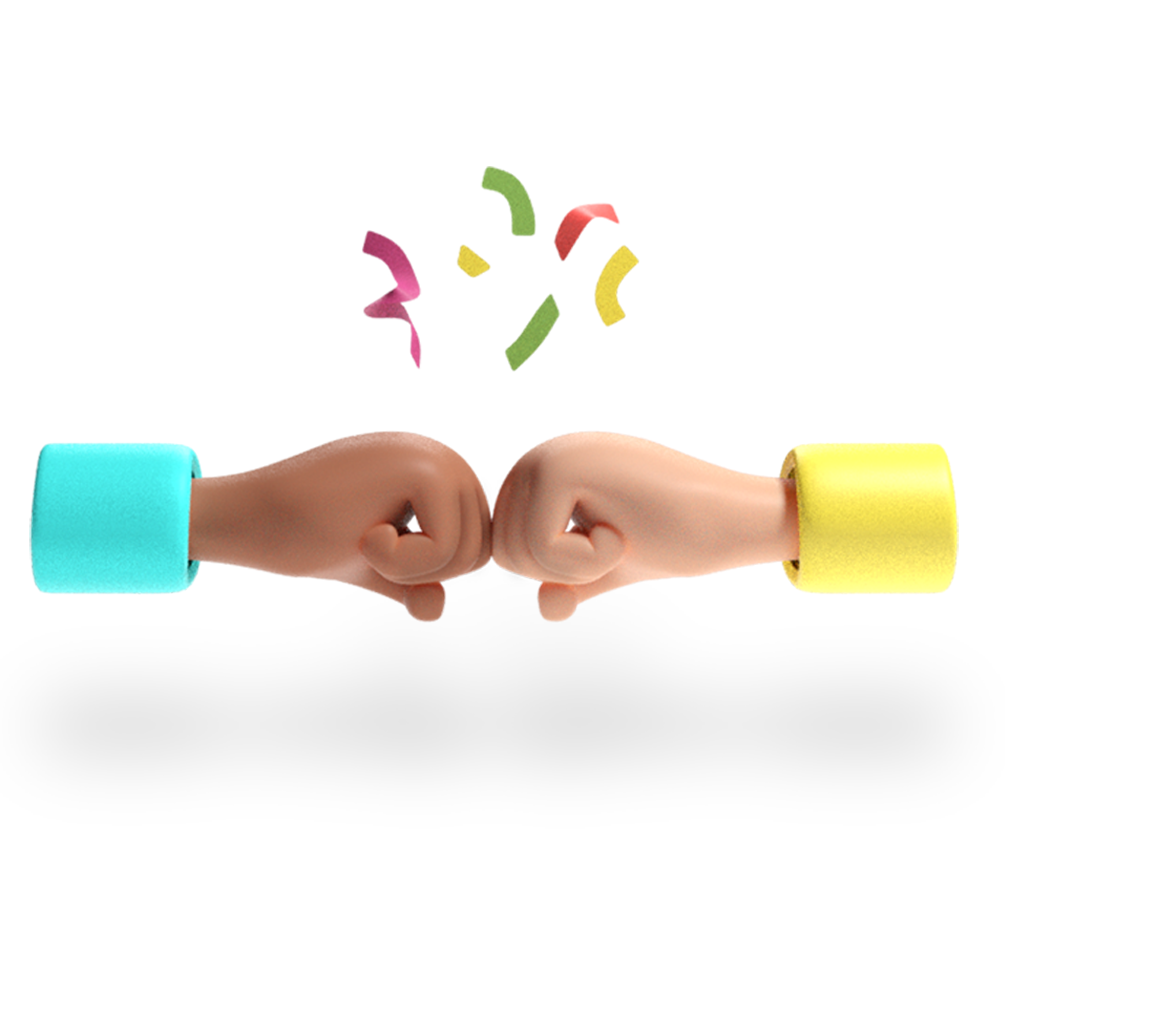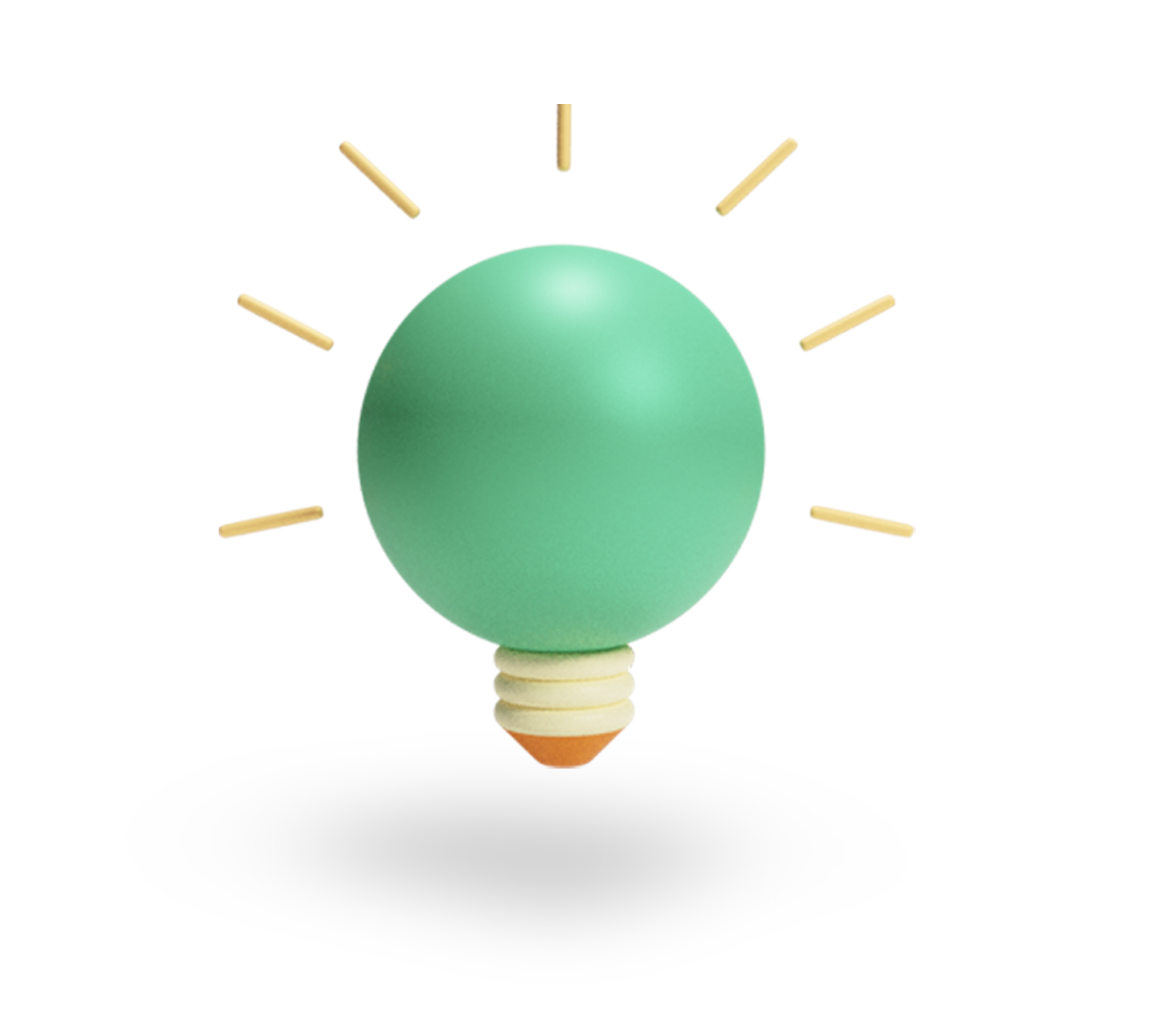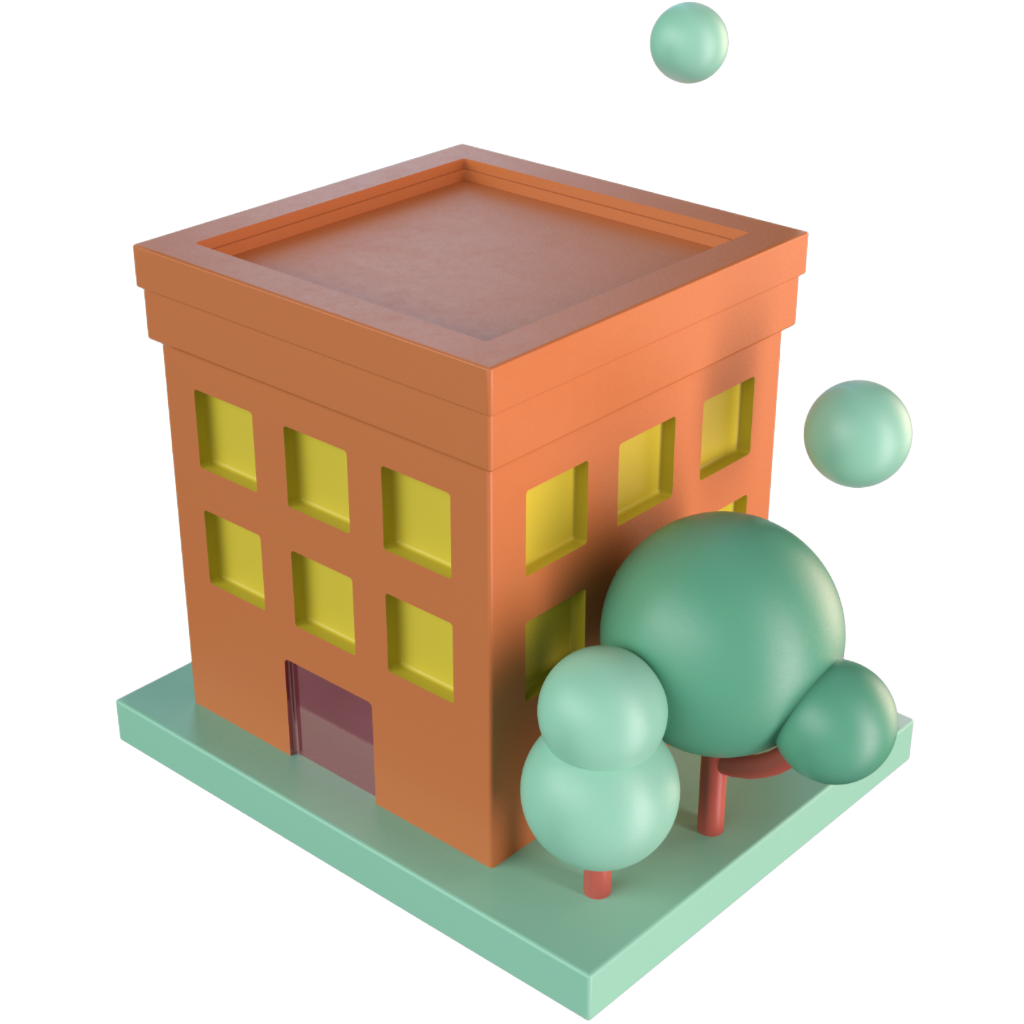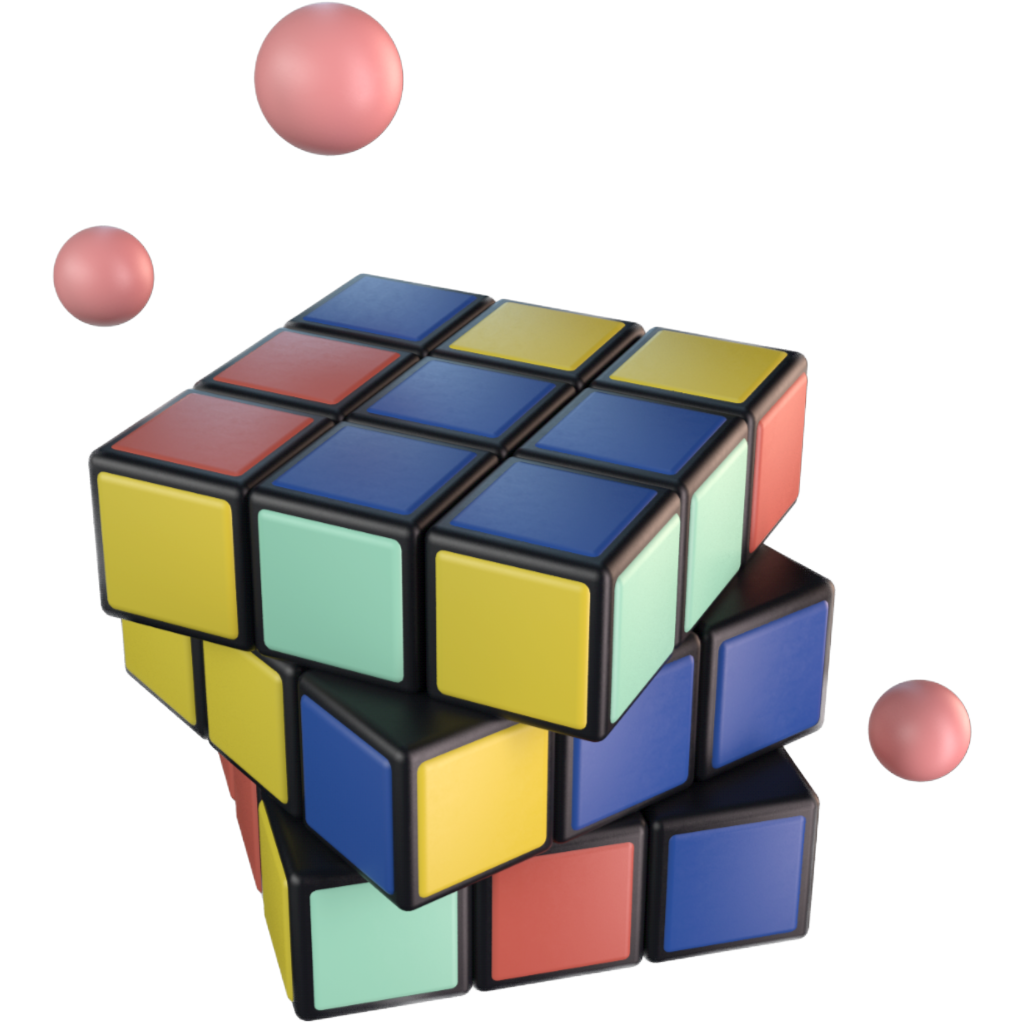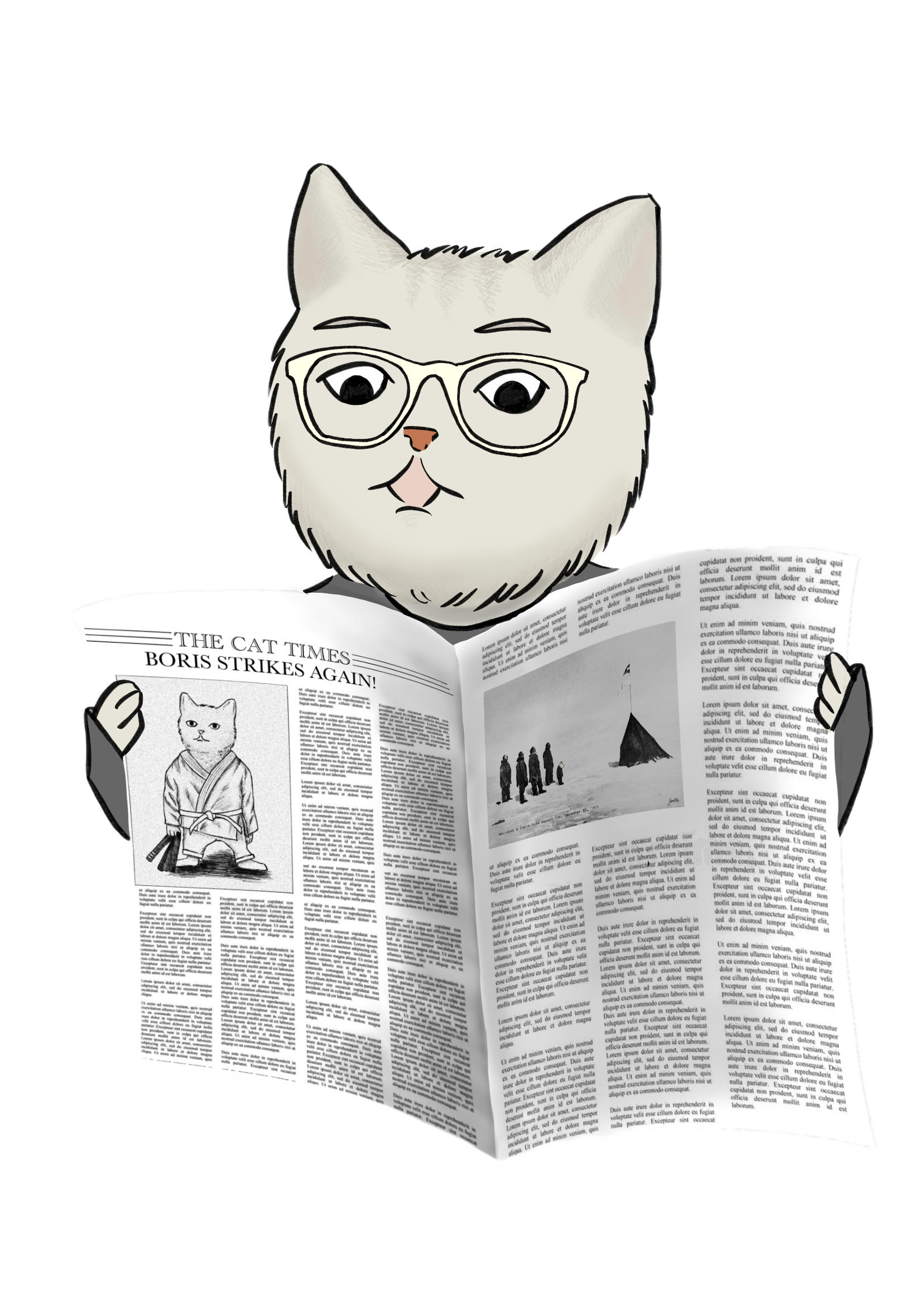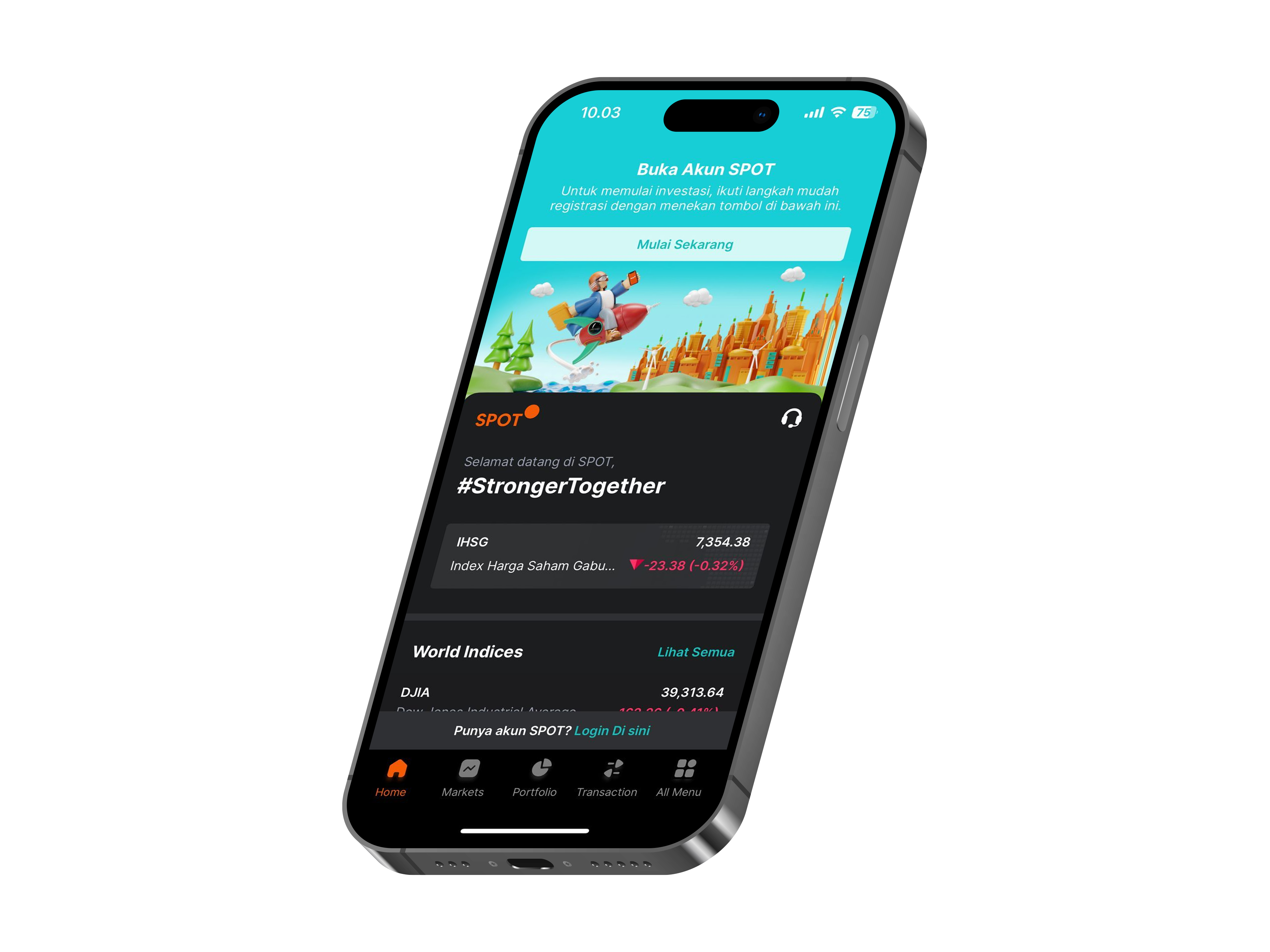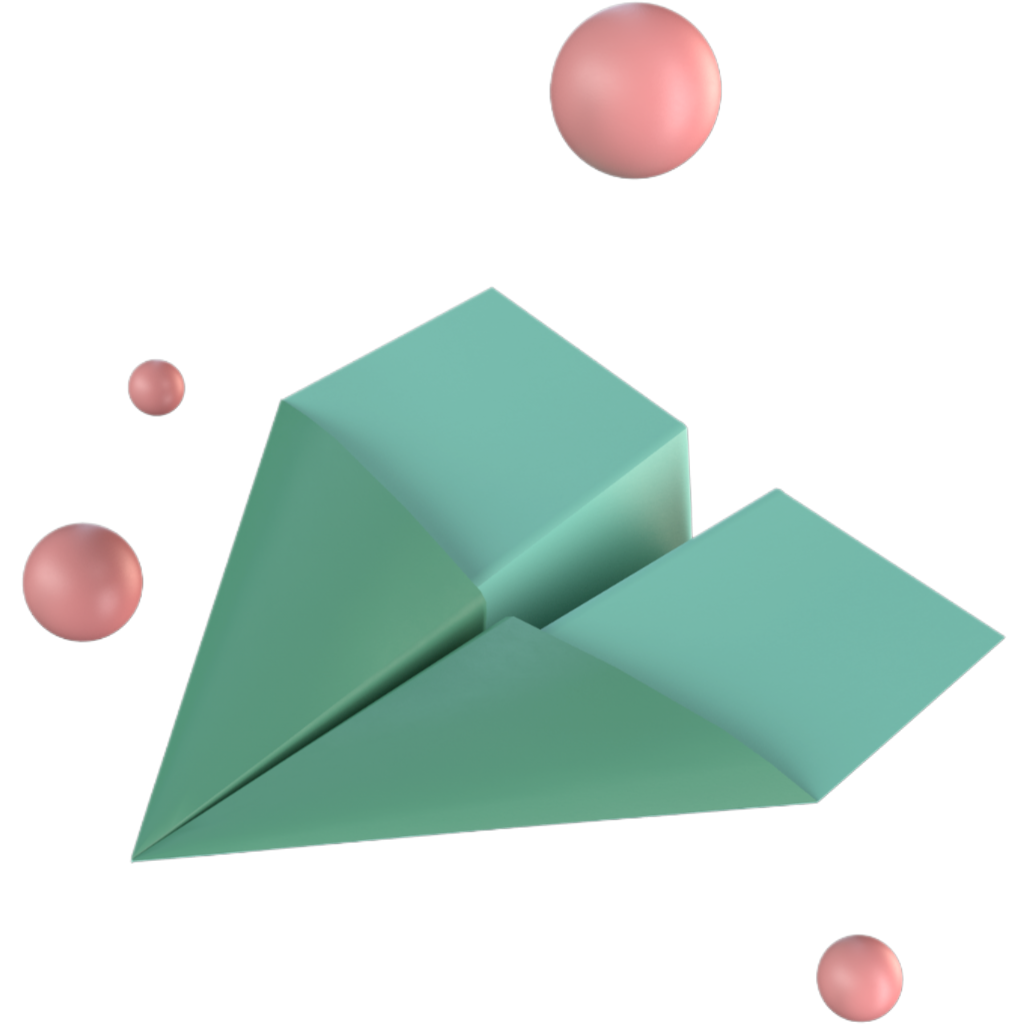Topik bicara pun bisa soal banyak hal. Dari topik inflasi, menyeberang ke topik sekolah anak, sampai wisata kuliner yang sedang ngehit, ia seolah tahu segalanya. Ia juga tahu kapan harus bicara apa dan kapan harus berhenti. Bahasa kekiniannya: smooth. Kalau saja dulu pernah belajar ilmu keuangan atau ekonomi, mungkin ia sudah jadi pialang saham atau ekonom ternama.

Sopir ojol berhenti di gedung Departemen Kesehatan. Aku bertanya apa dia tahu Marriott, dijawabnya pendek, “Tahu.”
“Ini Marriott bukan?” tanyaku lebih lanjut.
Dijawab, “Bukan, Pak. Ini Departemen Kesehatan, tapi sama Google Map suruh masuk sini.” Ia menjawab dengan percaya diri yang tidak kalah dengan The Fed yang di awal tahun lalu bilang inflasi hanya perkara transitory saja.
Sopir ojol, yang tahu persis kami tidak sedang berada di Marriott, masih bersemangat untuk membuktikan bahwa aplikasi tidak sedang salah. Bertanyalah ia pada satpam kompleks, “Ini Marriott Pak?”
Dijawab oleh satpam dengan muka masam, seolah sedang sambil mengunyah mangga muda yang dipetik prematur. “Tuh Pak baca, tulisan besar-besar, Departemen Kesehatan.”
Pak sopir ojol pun terdiam, lalu bergumam tidak jelas. Mungkin gumaman itu ditujukan pada dirinya sendiri, menyalahkan diri sendiri. Lantas ia melanjutkan perjalanan ke Marriott Kuningan. Kepalaku terasa sedikit berputar tatkala memperhatikan bahwa ia masih juga melirik aplikasi yang tertempel di sebelah roda setir mobil. Untuk apa? Toh ia tahu di mana lokasi persis Marriott dan aplikasi baru saja salah tujuan. Entah apa penjelasan logisnya.
Tapi sopir ojol tadi memang menyenangkan. Buktinya dengan segala bentuk keanehan tadi, emosiku masih datar-datar saja. Tidak semua sopir ojol punya soft skill humor dan sopan-santun yang sama. Pengalamanku dengan sopir ojol lain mirip-mirip. Serupa tapi tak sama. Bedanya, kali ini bermuara pada rasa kesal yang sempat merusak hari.
Hari itu, dalam perjalanan dari sebuah kedai kopi ke kantor, aku sempat berinteraksi dengan seorang sopir ojol yang bahkan lebih radikal dalam membela aplikasi andalan. Mata sang sopir begitu melekat ke aplikasi di hape, sampai-sampai tanpa ia sadari beberapa kali hampir menyerempet sepeda motor di sebelah kanan dan kiri mobil, tanpa diskriminasi.
Aku coba ingatkan “Pak, tolong lihat jalan, hampir loh kita serempet sepeda motor barusan. Jangan lihat ponsel terus, Pak.”
“Saya lagi lihat petunjuk jalan di aplikasi, Pak,” katanya membela diri.
“Apa yang mau dilihat? Belokan juga nggak ada kan, Pak, cuman ada pilihan lurus.” Aku mencoba beragumentasi, mungkin mood berdebat sedang hadir.
“Iya, memang sama aplikasinya juga disuruh lurus,” katanya, masih membela diri,
Sampai di sini nafsu berdebatku pun luntur seketika. Rasanya ingin cepat sampai tujuan saja.
Beberapa menit kemudian, sopir ojol merapat ke sebelah kanan jalan, bersiap untuk belok ke kanan. Aku cepat berusaha memberitahu bahwa itu langkah yang salah. “Pak, jangan belok kanan yang ini. Lurus saja lantas U-turn, mutar di depan.”
“Sama aplikasinya suruh belok kanan, Pak,” bantahnya.
“Jangan, Pak. Ambil putar balik berikutnya…” aku mencoba balik membantah.
“Nggak, Pak, sama aplikasi suruh belok kanan, ntar sudah langsung sampai,” kali ini ia bukan sekadar membela diri, tapi mulai juga membela aplikasinya.
“Aplikasinya salah, Pak,” kataku, mulai terbakar emosi. Mulai kesal pada agama aplikasi ini.
“Enggak, Pak. Mungkin alamatnya yang salah (sambil konfirmasi alamat),” katanya, membela aplikasi secara emosional.
“Alamatnya benar, aplikasi yang salah,” aku tidak mau mengalah begitu saja.
“Enggak Pak,” kali ini tanpa argumen, mungkin sebagai bentuk iman pada agama aplikasi.
“Pak, saya yang ngantor di sana loh. Tiap hari ke sana. Tolong putar di depan,” kataku memaksa.
“Baik kalau Bapak maunya begitu,” ujarnya. Jelas-jelas merasa terpaksa.
Akhirnya kami tiba di tujuan.
“Nah, tadi kalau Bapak belok kanan sesuai aplikasi, sampainya di sana. Salah kan?” Masih saja kulanjutkan debat ini.
“Enggak, Pak, mungkin alamatnya yang salah ya,” katanya, seperti tidak mendengarkan. Bentuk iman yang luar biasa pada aplikasi pujaan, yang membuatku kian gemas.
Di titik itu, kuputuskan untuk tidak mengajukan lagi keberatan dan perlawanan. Tiba-tiba aku memusatkan perhatian pada kultus aplikasi, yang mereduksi akal sehat dan pengetahuan. Tidak terbayang kalau suatu hari nanti kecerdasan buatan (AI) telah mengambil alih kontrol atas banyak aplikasi. Pasti makin banyak saja jumlah pemuja aplikasi.

Tidak hanya berita. Untuk urusan berbincang, atau sekadar mengucapkan selamat tahun baru, aplikasi chat juga menjadi andalan. Seakan chat di aplikasi bisa menggantikan perbincangan fisik. Tiba-tiba ada kesadaran bahwa aku pun ternyata seorang pemuja aplikasi. Yang juga sering melumpuhkan nalar dan mereduksi akal sehat.
Dan kalau bicara soal hilangnya akal sehat, di duniaku di bidang pasar modal, aku juga sedang mengingatkan diri sendiri. Pemikiran ala textbook dan pengalaman masa lalu seringkali menjadi beban bagiku untuk dapat berpikir secara bebas. Textbook dan pengalaman kita berfungsi sebagaimana aplikasi bagi sopir ojol.
Mungkin karena belajar dari textbook dan mereguk pengalaman itu butuh pengorbanan, kita tidak serta merta rela kehilangan iman bahwa mereka bisa menjadi penunjuk jalan yang baik di pasar saham. Padahal dunia mungkin telah berubah secara dramatis.
Buku textbook yang dibaca mahasiswa S1 dan S2 seringkali dihasilkan dari disertasi doktoral, yang mungkin ditulis satu dekade yang lalu. Jadi ikut textbook secara kaku itu seringkali berarti ketinggalan zaman.
Juga terlalu mengandalkan pengalaman yang lama, seringkali bermuara pada ketinggalan jaman. Apalagi semakin hari bumi terasa berputar makin cepat.
Misalnya di era ini, di zaman di mana dunia bergeser dari era unipolar (satu poros superpower) ke multipolar (beberapa poros dunia), tindakan dari para pemimpin negara seringkali menjadi jauh lebih penting daripada tindakan bank sentral dunia. Padahal dulu menjadi pendengar setia chair bank sentral Amerika Alan Greenspan, sudahlah cukup. Pengalaman dari era unipolar mungkin menjadi kurang relevan.
Textbook dan pengalaman kita di market itu bagaikan aplikasi bagi sopir ojol.
Pertanyaan yang terbersit adalah bagaimana menjadi sopir ojol yang sukses. Dan bagaimana menjadi insan pasar modal yang sukses.
Ojol yang sukses mungkin gabungan antara membaca aplikasi, pengalaman di jalan, akal sehat, mendengarkan masukan pelanggan, dan kemauan untuk belajar peta dan tempat-tempat destinasi baru.
Analis pasar modal yang sukses mungkin gabungan antara mengerti teori dunia ekonomi dan keuangan, pengalaman di pasar, akal sehat, kebersediaan untuk menjadi pendengar yang baik, dan kemauan untuk terus belajar dan bertumbuh.
Rasa kesal pada sopir ojol pemuja aplikasi terasa luntur. Digantikan dengan rasa nikmat atas momen yang ada. Yang lebih berkesadaran, untuk tidak menjadi pemuja aplikasi, textbook, ataupun pengalaman kita.